Perkembangan Peserta Didik: Perkembangan Kemandirian
PERKEMBANGAN
KEMANDIRIAN PESERTA DIDIK
A. Pengertian
Kemandirian
Istilah ”kemandirian”
berasal dari kata dasar diri yang mendapat awalan ”ke” dan akhiran ”an”, kemudian membentuk satu
kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata dasar
”diri”, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan
tentang perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers disebut
dengan istilah self, karena diri itu merupakan inti dari kemandirian. Konsep
yang sering digunakan atau berdekatan dengan kemandirian adalah autonomy.
Menurut Chaplin
(2002), otonomi atau kemandirian adalah kebebasan individu manusia untuk
memilih menjadi kesatuan yang bisa
memerintah, menguasai, dan menentukan dirinya sendiri. Sedangkan Seifert dan
Hoffnung (1994) mendefinisian otonomi atau kemandirian sebagai “the ability to
govern and regulate one’s own thoughts,feelings, and actions freely and
responssibly while overcoming feeling of shame and doubt”
Erikson (1989),
menyatakan kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orangtua dengan
maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego yaitu
merupakan perkembangan kea rah individualitas yang mantap dan berdiri sendiri.
Kemandirian biasanya ditandai dengan kemapuan menentukan nasib sendiri, kreatif
dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri,
dan lain lain. Kemandirian merupakan suatu sikap otonomi dimana peserta didik
secara relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat dan keyakinan orang
lain. Dengan otonomi tersebut, peserta didik diharapkan akan lebih bertanggung
jawab terhadap dirinya sendiri.
Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa kemandirian atau otonomi adalah kemampuan untuk
mengendalikan dan mengatur pikiran, perasaan dan tindakan sendiri secara bebas
serta berusaha sendiri untuk mengatasi perasaan-perasaan malu dan
keragu-raguan.
Secara singkat
dapat disimpulkan bahwa kemandirian mengadung pengertian :
a.
Suatu kondisi dimana seseorang memiliki hasrat
bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri.
b.
Mampu mengambil keputusan dan inisiatif
untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
c.
Memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan
tugas-tugasnya.
d.
Bertanggung jawab atas apa yang
dilakukannya.
B. Bentuk-Bentuk
Kemandirian
Robert Havighurst
(1972) membedakan kemandirian atas empat bentuk kemandirian yaitu:
a)
Aspek Emosi, aspek ini ditunjukan dengan
adanya kemampuan untuk dirinya mengatur emosinya sendiri.
b)
Aspek Ekonomi, aspek ini ditunjukan dengan
adanya kemampuan untuk mengatur dan mengelola kebutuhan dirinya sendiri secara
ekonomis.
c)
Aspek Intelektual, aspek ini ditunjukan
dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.
d)
Aspek Sosial, aspek ini ditunjukan dengan
kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung
kepada orang lain.
Semantara itu, Steiberg (1993) membedakan
karakteristik kemadirian atas tiga bentuk, yaitu :
1) Kemandirian
emosional (emotional autonomy)
2) Kemandirian
tingkah laku ( behavioral autonomy ) .
3) Kemandirian
nilai (value autonomy )
Lengkapnya Steinberg menulis :
“The first emotional autonomy-that aspec of
independence related to changes in the individual’s close
relationship,especially with parent. The second behavioral autonomy-the
capacity to make independent decisionis and follow trough with them. The third
characterization involves and aspec of independence referred to us value
autonomy-wich is more than simply being able to resist preassures to go along
with the demands of other, its means having a set a principles about right and
wrong, about what is important and what is not.”
Kutipan di atas menunjukan karakteristik dari
ketiga aspek kemandirian, yaitu :
a.
Kemandirian emosional yakni aspek
kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar
individu,
b.
Kemandirian tingkah laku, yakni suatu
kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain
dan melakukannya secara bertanggung jawab.
c.
Kemandirian nilai, yakni kemandirian
memaknai suatu hal tentang benar dan salah, tentang yang penting dan apa yang
tidak penting.
C. Tingkatan
dan Karakteristik / Ciri-Ciri Kemandirian Peserta Didik
Sebagai suatu
dimensi psikologi yang kompleks, kemandirian dalam perkembangannya memiliki
tingkatan-tingkatan. Perkembangan kemandirian seseorang berlangsung secara
bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan kemandirian tersebut. Menurut
Lovinger (dalam Sunaryo Kartadinata,1988), mengemukakan tingkatan kemandirian
dan karakteristiknya, yaitu:
1. Tingkat pertama,
adalah tingkatan implusif dan melindungi diri. Tingkatan ini mempunyai
ciri-ciri sebagai berikut :
a)
Peduli terhadap kontrol dan keuntungan
yang dapat diperoleh dari interaksinya dengan orang lain.
b)
Mengikuti aturan secara spontanistik dan
hedonistic.
c)
Berfikir tidak logis dan tertegun pada
cara berfikir tertentu ( stereotype).
d)
Cenderung melihat kehidupan sebagai
zero-sum games.
e)
Cenderung menyalahkan dan mencela orang
lain serta lingkunganya.
2.
Tingkat kedua, adalah
konformistik. Ciri-cirinya adalah :
a) Peduli terhadap penampilan diri dan
penerimaan social.
b) Cenderung berfikir stereotype dan klise.
c) Peduli akan konformitas terhadap aturan
eksternal.
d) Bertindak dengan motif yang dangkal untuk
memperoleh pujian.
e) Menyamakan diri dalam ekspresi emosi dan
kurangnya intropeksi.
f) Perbedaan kelompok didasarkan atas ciri-ciri
eksternal.
g) Takut tiadak diterima kelompok.
h) Tidak sensitif terhadap keindividualan.
i) Merasa berdosa jika melanggar aturan.
3.
Tingkatan ketiga, adalah
tingkat sadar diri. Ciri-cirinya adalah:
a) Mampu berfikir alternatif.
b) Melihat harapan dan berbagai kemungkinan
dalam situasi.
c) Peduli untuk mengambil mamfaat dari
kesempatan yang ada.
d) Menekankan pada pentingnya memecahkan
masalah.
e) Memikirkan cara hidup.
f) Penyesuaian terhadap situasi dan peranan.
4.
Tingkat keempat, adalah
tingkat saksama (conscientious). Ciri-ciri nya adalah :
a)
Bertindak atas dasar nilai-nilai internal.
b)
Mampu melihat diri sebagai pembuat ilihan
dan pelaku tindakan.
c)
Mampu melihat keragaman emosi, motif, dan
perspektif diri sendiri maupun orang lain.
d)
Sadar akan tanggung jawab.
e)
Mampu melakukan kritik dan penilaian diri.
f)
Peduli akan hubungan mutualistik
g)
Memiliki tujuan jangka panjang.
h)
Cenderung melihat peristiwa dalam konteks
sosial.
i)
Berfikir lebih kompleks dan atas dasar
pola analisis.
5.
Tingkat kelima, tingkat
individualitas. Ciri-cirinya:
a) Peningkatan
kesadaran individualitas.
b) Kesadaran
akan konflik emosional antara kemandirian dan ketergantungan.
c) Menjadi
lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain.
d) Mengenal
eksistensi perbedaan individual.
e) Mampu
bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupan.
f) Memberi
kehidupan internal dengan kehidupan luar dirinya.
g) Mengenal
kompleksitas diri.
h) Peduli
akan perkembangan dan masalah-masalah sosial.
6.
Tingkat keenam, adalah tingkat
mandiri. Ciri-cirinya:
a) Memiliki
pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan.
b) Cenderung
bersikap realistik dan objektif terhadap diri sendiri dan orang lain.
c) Peduli
terhadap pemahaman abstrak, seperti keadilan sosial.
d) Mampu
mengintekresikan nilai-nilai yang bertentangan.
e) Toleran
terhadap ambiguitas.
f) Peduli
akan pemenuhan diri (self-fulfilment).
g) Ada
keberanian untuk menelesaikan konflik internal.
h) Responssif
terhadap kemandirian orang lain.
i) Sadar
akan adanya saling ketergantungan dengan orang lain.
j) Mampu
mengekspresikan perasaan dengan penuh keyakinan dan keceriaan.
D.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian
Adapun faktor-faktor yang
mempengaruhi kemandirian adalah :
1.
Gen atau keturunan orang tua.
Orang tua yang
memiliki sifat kemandirian tinggi seringkali menurunkan anak yang memiliki
kemandirian juga. Namun, faktor keturunan ini masih menjadi perdebatan karena
ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya bukan sifat kemandirian orang tuanya
itu menurun kepada anaknya, melainkan sifat orang tuanya muncul berdasarkan
cara orang tua mendidik anaknya.
2.
Umur
Anak mulai
menampakkan perilaku mandiri pada sekitar usia dua sampai tiga tahun.
Kemandirian pada usia kanak-kanak ditandai dengan adanya kemampuan anak untuk
dapat makan sendiri, berpakaian sendiri dan ke kamar mandi sendiri. Anak
nantinya akan tumbuh menjadi remaja dimana ketika usia remaja anak berusaha
untuk lepas dari pengawasan orang tua dan mulai belajar memutuskan sendiri apa
yang baik untuknya. Jadi dengan bertambahnya umur maka seseorang akan semakin
tidak tergantung kepada orang lain dan mampu secara mandiri menentukan arah
hidupnya sendiri.
3.
Jenis kelamin
Perbedaan
perlakuan yang diberikan oleh orang tua menyebabkan perbedaan terbentuknya
kemandirian antara remaja putra dengan remaja putri. Perbedaan kemandirian
remaja putra dan putri juga disebabkan karena adanya perbedaan stereotipe bahwa
remaja putra dan remaja putri memiliki peranan yang berbeda di masyarakat.
Menurut penelitan Kimmel (dalam Soetjipto, 1989) menunjukkan bahwa masyarakat
menganggap remaja putri terlihat kurang mandiri daripada remaja putra karena
remaja putri lebih dipandang lebih bersikap kurang percaya diri, tidak ambisius
dan sangat tergantung. Berbeda dengan remaja putra yang dipandang lebih
dominan, aktif, lebih percaya diri dan ambisius. Jadi perbedaan perlakuan dan
stereotipe antara peran pria dan wanita di dalam kehidupan bermasyarakat
membuat perbedaan dalam perkembangan kemandirian antara anak laki-laki dan perempuan.
4.
Pola asuh orang tua.
Cara orang tua
yang mengasuh atau mendidik anak akan mempengaruhi perkembangan kemandirian
anak. Orang tua yang terlalu banyak melarang atau mengeluarkan kata “jangan“
kepada anak tanpa disertai penjelasan yang rasional akan menghambat
perkembangan kemandirian anak. Sebaliknya, orang tua yang menciptakan suasana
aman dalam interaksi keluarganya akan dapat mendorong kelancaran perkembangan
anak. Demikian juga, orang tua yang cenderung sering membanding-bandingkan anak
yang satu dengan yang lainnya juga akan berpengaruh kurang baik terhadap
perkembangan kemandirian anak.
5.
Sistem pendidikan di sekolah.
Proses pendidikan
di sekolah yang tidak mengem-bangkan demokratisasi pendidikan dan cenderung
menekankan indoktrinasi tanpa argumentasi akan menghambat perkembangan
kemandirian anak. Demikian juga, proses pendidikan yang banyak menekankan
pentingnya pemberian sanksi atau hukuman (punishment) juga dapat menghambat
perkembangan kemandirian anak. Sebaliknya, proses pendidikan yang lebih
menekankan pentingnya penghargaan terhadap potensi anak, pemberian reward, dam
penciptaan kompetisi positif akan memperlancar perkembangan kemandirian anak.
6.
Sistem kehidupan di masyarakat.
Sistem kehidupan
masyarakat yang terlalu menekankan pentingnya hierarki struktur sosial, merasa
kurang aman atau mencekam serta kurang menghargai manifestasi potensi anak
dalam kegiatan produtif dapat menghambat kelancaran perkembangan kemandirian
anak. Sebaliknya, lingkungan masyarakat yang aman, menghargai ekspresi potensi
anak dalam bentuk berba-gai kegiatan, dan tidak terlalu hierarkis akan
merangsang dan mendorong perkembangan kemandirian anak.
E. Pentingnya
Kemandirian bagi Peserta Didik
Pengembangan
kemandirian menjadi sangat penting karena dewasa ini semakin terlihat
gejala-gejala negatif sebagai berikut :
1) Ketergantungan disiplin kepada kontrol dari
luar dan bukan karena niat sendiri secara ikhlas. Dewasa ini rasanya semakin
sulit menemukan kedisiplinan, baik di jalanan, di kantor, dan berbagai lembaga
atas situasi lain yang memang muncul secara ikhlas dari dalam hati nurani yang
bersih
2) Sikap tidak peduli terhadap lingkungan hidup,
baik lingkungan fisik maupun social. Gejala perusakan lingkungan, baik yang
daoat diperbarui maupun tidak diperbarui semakin tak terkendali, yang penting
mendapatkan keuntungan financial
3) Sikap hidup konformistik tanpa pemahaman dan
kompromistik dengan mengorbankan prinsip. Kecenderungan untuk mematuhi dan
menghormati orang lain semakin dilandasi bukan oleh hakikat kemanudiaan sejati
melainkan hanya karena atribut-atribut sementara yang dimiliki oleh orang lain.
Gejala-gejala
tersebut merupakan bagian kendala utama mempersiapkan individu-individu yang
mengarungi kehidupan masa mendatang yang semakin kompleks dan penuh tantangan.
Oleh sebab itu, perkembangan kemandirian peserta didik menuju kearah
kesempurnaan menjadi sangat penting untuk dilakukan secara serius, sistematis
dan terprogram. (Baharuddin. 2009)
F.
Perkembangan Kemandirian Peserta Didik dan Implikasinya bagi Pendidikan
Kemandirian
peserta didik adalah bakat kecakapan yang dimiliki peserta didik, ini sangat
berkaitan dengan pendidikan. Oleh sebab itu pendidikan di sekolah perlu
melakukan upaya-upaya pengembangan kemandirian peserta didik, diantaranya :
·
Mengembangkan proses belajar mengajar yang
demokratis, yang memungkinkan anak merasa dihargai.
·
Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif
dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah.
·
Memberi kebebasan kepada anak untuk
mengeksplorasi lingkungan , mendorong rasa ingin tahu mereka.
·
Peneriman positif tanpa syarat kelebihan
dan kekurangan anak, tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain.
·
Menjalin hubungan yang harmonis dan akrab
dengan anak.
Dengan semua itu,
maka akan terbentuk pribadi peserta didik yang mandiri. Yang juga implikasi
untuk keadaan dunia pendidikan yang akan semakin berkembang. (Baharuddin. 2009).
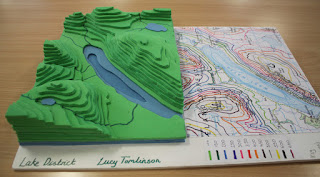
Komentar
Posting Komentar